Sistem Presidensial Punya Sejumlah Kelemahan, Ini Penjelasan Guru Besar Unair

Merdeka.com - Dalam kajian ilmu politik, sistem presidensial dinyatakan punya sejumlah kelemahan. Salah satunya potensi deadlock atau kebuntuan dalam hubungan antara legislatif dan eksekutif.
Demikian disampaikan guru besar ilmu politik Universitas Airlangga, Prof. Ramlan Surbakti, dalam diskusi online bertajuk 'Presidensial vs Parlementer' yang digelar DPP PSI, Rabu 21 April 2021.
Ramlan menukil penelitian Juan Linz dan Arturo Valenzuela yang dibukukan dalam The Failure of Presidential Democracy (1994). Karya itu tersebut menyebut sejumlah kelemahan sistem presidensial.
-
Bagaimana proses pemakzulan presiden? Proses pemakzulan presiden di Indonesia melibatkan tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR. Mekanisme ini diatur secara rinci dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
-
Siapa yang menilai kapabilitas wakil rakyat? "Warga Jakarta sudah pintar, bisa menilai kapabilitas seseorang hingga dipercaya masyarakat," papar Uya Kuya.
-
Apa penyebab perselisihan hasil pemilu? Perselisihan hasil pemilu merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik yang timbul terkait dengan proses pemilihan umum.
-
Siapa presiden RI pertama? Merupakan presiden pertama RI yang sering disebut sebagai bapak proklamator.
-
Bagaimana masa jabatan presiden diatur sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Bagaimana dinasti politik berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia? Didominasi Orang-Orang Politik Arga melihat, sejauh ini partai besar sekalipun didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik, bukan dari masyarakat luas. Bahkan jabatan strategis dengan mudah diperoleh dari hubungan keluarga dan kerabat. Dampaknya semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa untuk ikut andil dalam politik.
Pertama, sistem presidensial bisa menyebabkan deadlock (kebuntuan) dalam hubungan antara legislatif dan eksekutif. Karena baik anggota parlemen dan presiden sama-sama dipilih rakyat.
"Terjadi kebuntuan antara presiden dengan parlemen, jika tidak tersedia solusi demokratis. Kalau sistem parlementer ada solusinya: parlemen bisa memberi mosi tidak percaya kepada kabinet, atau perdana menteri membubarkan parlemen dan membuat Pemilu baru," kata Ketua KPU periode 2004–2007 itu.
Kedua, imbuhnya, masa jabatan tetap presiden dalam sistem presidensial juga jadi sumber masalah. Pasalnya, belajar dari pengalaman Amerika Serikat, jika presiden tidak dapat melanjutkan tugasnya maka yang akan menggantikan adalah wakil presiden yang belum tentu kompeten, karena paket presiden dan wakil presiden ditentukan oleh partai dan akan bekerja sama sampai masa jabatan habis.
Ada pun sistem presidensial, ucap Ramlan, ditengarai turut melahirkan 'one man show', karena presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal itu merujuk pada kewenangan presiden yang relatif otonom untuk membuat dan menentukan kebijakannya sendiri. Akibatnya, kebijakan presiden sulit diprediksi.
“Eksekutif (presiden) yang kuat dan stabil, karena presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus, sehingga menimbulkan kecurigaan terjadinya personifikasi kekuasaan. Bahkan dikatakan, kekuasaan presiden cenderung tidak dapat diprediksi,” terangnya.
Keempat, pemilihan presiden dalam sistem presidensial cenderung menerapkan “winner takes all”. Distribusi kekuasaan yang tidak merata itu menyisakan polarisasi dan ketegangan di tengah masyarakat.
“Karena yang menang dapat jabatan dan yang kalah tidak mendapat apa-apa, maka tidak ada peluang akan terjadinya perubahan politik sehingga menyimpan ketegangan dan polarisasi,” katanya.
Kelima, kelebihan sistem parlementer dari sistem presidensial terletak pada akuntabilitas pelaksanaan kebijakan publik yang lebih demokratis. Kelemahan presidensialisme yang terakhir adalah, karena kabinet dibentuk dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden, maka tidak ada menteri yang independen (terpisah) dari presiden.
Studi Juan Linz dan Arturo Valenzuela ini kemudian dikritisi para ilmuwan politik lain. Pertama, bentuk sistem presidensial tidak homogen. Ada sejumlah variasi kelembagaan.
Di Indonesia, presidensialisme bukan fotokopi Amerika Serikat. Hal yang sama terjadi di sistem parlementer. Malaysia atau India bukan fotokopi yang di Inggris. Karena itu, kata Ramlan, presidensialisme dan parlementarisme tidak bisa dilihat secara dikotomik.
“Selanjutnya, presidensialisme akan menghasilkan divided government jika, pertama, ada banyak partai, seperti di Indonesia. Kedua, pemilu legislatif dan eksekutif terpisah waktunya. Ketiga, lebih menggunakan sistem pemilu proporsional ketimbang mayoritarianisme atau plurality,” ungkapnya.
Fakta lain, secara statistik, kebuntuan pemerintahan hanya terjadi di sepertiga dari seluruh kasus pemerintahan presidensialisme. Pada kenyataannya, deadlock juga terjadi di sistem parlementer. Yaitu, ketika tidak ada parpol yang menjadi mayoritas di parlemen. Akibatnya, kabinet mudah diberi mosi tidak percaya oleh parlemen. Pemerintahan buntu dan pemilu harus digelar lagi.
Hal lain, koalisi juga terjadi di sistem parlementar. Karena partai juga berkepentingan untuk mendapat kepercayaan dari pemilih. Caranya adalah dengan masuk kabinet, bukan menjadi oposisi.
“Di Indonesia, kebuntuan hubungan eksekutif – legislatif tidak pernah terjadi. Sejak Pemilu 1999, belum pernah ada satu RUU atau RAPBN yang ditolak DPR. Apalagi sekarang, sejak beberapa tahun terakhir, Baleg DPR dan dan Menkum HAM di awal menyepakati agenda legislatif. Dengan agenda legislatif, kemungkinan veto eksekutif tidak terjadi,” kata Ramlan.
Ramlan juga merespons pertanyaan soal perlu atau tidaknya pemberlakuan presidential threshold pada Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, ambang batas pencalonan presiden masih perlu, namun tidak boleh dipatok tinggi untuk membuka ruang kompetisi yang lebih terbuka.
“Harus ada presidential threshold, tapi saya bilang jangan setinggi itu agar calonnya tidak hanya dua,” tutupnya.
Sementara itu, Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti mengajak publik untuk memikirkan ulang sistem parlementer, termasuk menggelar diskusi yang melibatkan para pakar.
PSI ingin mendorong percakapan politik menjadi lebih substantif dan sesuai kepentingan publik. Kepentingan publik dalam hal ini adalah bagaimana pemerintahan berjalan efektif dan di sisi lain demokrasi terjaga.
“Kami beranggapan, setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang,” kata Dea.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Kampus bergerak menuntut Presiden menghentikan penyalahgunaan kekuasaan
Baca Selengkapnya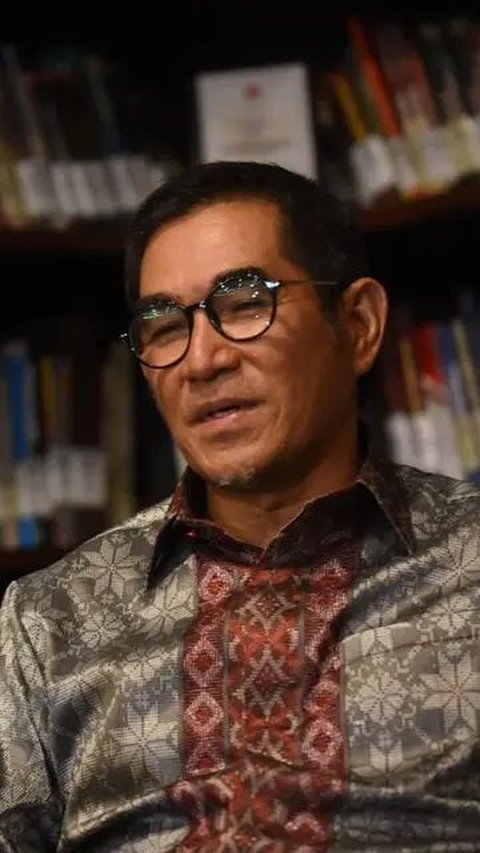
Mekanisme pemilihan langsung presiden oleh rakyat dinilai masih lebih baik
Baca Selengkapnya
Hasto ingin agar segala sesuatunya harus dicermati serta harus dikaji dengan bersamaan.
Baca Selengkapnya
Pimpinan MPR bertemu Jokowi di Istana Merdeka Jakarta hari ini, Jumat (28/6).
Baca Selengkapnya
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca Selengkapnya
Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca Selengkapnya
Senior Demokrat tak setuju dengan usulan amandemen UUD 1945 untuk mengubah Pemilihan Presiden Kembali lewat MPR.
Baca Selengkapnya
Di era reformasi, butuh proses panjang dan berliku untuk melengserkan Presiden dari tampuk kekuasaan.
Baca Selengkapnya
"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan mantan Ketua Ketua MPR 1999-2004, Amien Rais usai bertemu dengan pimpinan MPR di kompleks parlemen.
Baca Selengkapnya
Peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini sebuah rangkaian dari menurunya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Watimpres wajib memberikan pertimbangan kepada Presiden
Baca Selengkapnya