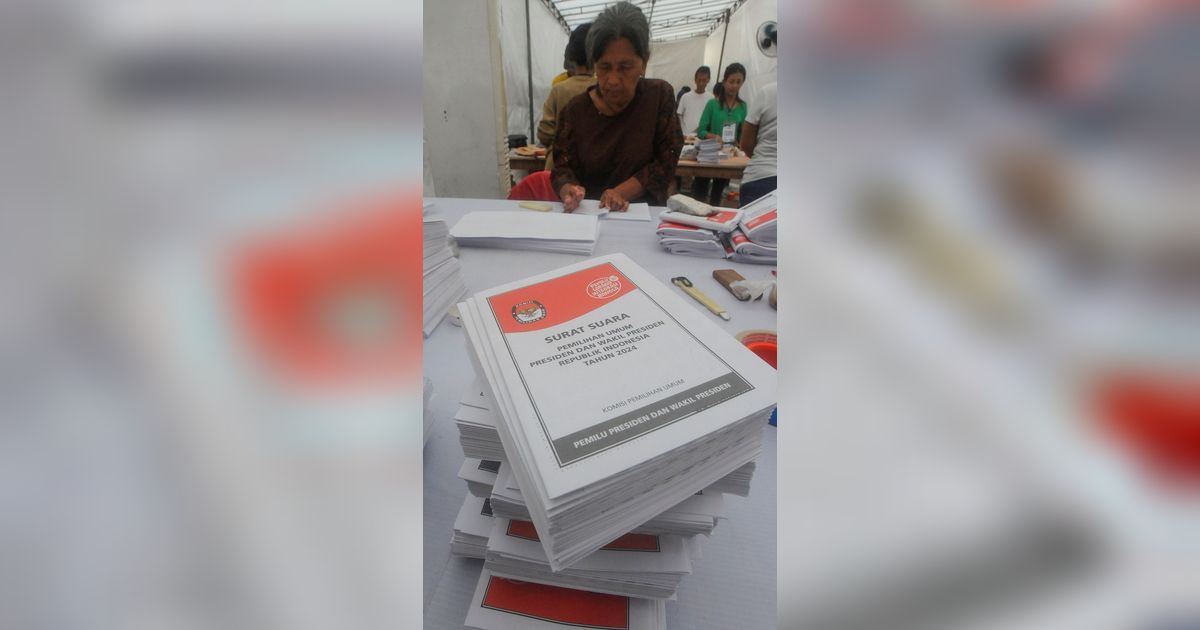BPIP Kumpulkan Para Pakar Bahas Paradoks Beragama di Indonesia, Hanya Formalitas?
Agama saat ini lebih sering digunakan sebagai alat politik dan ekonomi.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kembali menggelar focus group dicussion (FGD) menyoal kerapuhan etika penyelenggara negara. Salah satu yang menjadi sorotan adalah perilaku sosial masyarakat di Indonesia.
Dewan Pengarah BPIP, Prof Amin Abdullah mengatakan, terjadi paradoks antara keagamaan dan indeks perilaku korupsi. Dia heran, negara yang tingkat religiulitasnya tinggi justru perilakunya cenderung lebih koruptif. Ketimbang negara yang tingkat religusnya Kecil.
Prof Amin mengungkapkan, Indonesia dan Brasil memiliki tingkat keberagamaan yang tinggi. Dimana Indonesia capai 96 persen. Tapi sayangnya, dua negara itu justru indeks perilaku korupsinya kecil.
“Dari angka 100 Indonesia 34 dari angka 100, Brasil 38,” kata Prof Amin saat membuka FGD yang digelar di Kota Ambon, Maluku, Jumat (20/9).
Menurut dia, data tersebut membuat paradoks, Sementara, negara yang warganya kurang menekankan agama justru indeks korupsinya tinggi.
“Australia cuma 19 persen, tapi skor korupsinya 75 dari 100. Prancis keberagamaannya itu cuma 15. Tapi antikorupsi masyarakatnya capai 72 dari 100,” tegas dia.
Prof Amin mengaku, FGD ini diperlukan untuk menjawab data tersebut. Bagaimana tantangan kehidupan dalam bermasyarakat bernegara.
“FGD ingin menyerap masukan gagasan pandangan juga usulan-usulan dari para narasumber termasuk usulan apa kepada BPIP,” tegas Prof Amin.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Andar Nubowo mengungkapkan, agama saat ini lebih sering digunakan sebagai alat politik dan ekonomi.
“Agama hanyalah alat untuk diperlemah atau dipergunakan untuk status quo politik dan ekonomi,” ujar dia.
Andar juga menyoroti adanya favoritisme terhadap agama-agama tertentu, yang dianggap memperburuk kondisi moralitas publik. Dengan agama digunakan sebagai instrumen politik, peran agama dalam menjaga etika dan moralitas masyarakat melemah, menyebabkan terjadinya apa yang disebut Andar sebagai tragedi etika dan moralitas publik.
Baginya, agama tidak lagi mampu menjadi kekuatan moral yang independen, tetapi justru menjadi alat untuk kepentingan politik praktis. Padahal, dalam sejarahnya, peran agama di Indonesia selalu dijadikan basis etika dalam kehidupan berbangsa, bahkan ikut menjadi instrument mencapai kemerdekaan Indonesia.
Di negara-negara barat, jelas Andar, dikembangkan konsep mengenai civil religion yang berasal dari nilai universal dan nilai profetik agama yang ditumpukan atau disandarkan pada nilai-nilai agama yang nilai universal sekaligus digabungkan pada prinsip sekular modern di Barat.
“Ini saya kira perlu jadi renungan kita semua bagaimana negara kita yang berideologi Pancasila perlu melakukan radikalisasi Pancasila, sebagaimana yang disebutkan Kuntowijoyo. Jadi bagaiman jadikan pancasila sebagai ideologi dasar kita. Sehingga pancasila bukan Cuma batang tubuh, tapi juga kaki-kaki kita,” katanya.
Kapitalisasi Agama
Akademisi IAIN Ambon, Abidin Wakano melihat agama-agama di Indonesia kini kehilangan 'elan vital' atau semangat profetiknya. Menurut Wakano, agama sudah tidak lagi memiliki daya untuk menuntun masyarakat menjawab berbagai tantangan sosial dan justru terjebak dalam industrialisasi politik identitas.
“Oligarki, kapitalisasi agama membuat agama-agama ikut terperangkap dalam sistem oligarki,” tegas Wakano, yang menyoroti kekuatan ekonomi dan politik elit turut menggerus otoritas moral agama.
Wakano menilai sejak Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019, agama telah digunakan secara luas dalam narasi politik identitas. Penggunaan agama dalam politik ini menyebabkan segregasi sosial, memecah masyarakat berdasarkan identitas agama, dan memunculkan mentalitas in-group dan out-group.
Agama yang seharusnya berperan sebagai pedoman etis dan moral bagi masyarakat, kini terperangkap dalam dinamika politik praktis yang mengaburkan nilai-nilai substansial agama.
Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ahmad Najib Burhani mengungkapkan, adanya paradoks dalam keberagamaan di Indonesia. Salah satunya pluralitas yang terbatas.
Menurut Burhani, meskipun Indonesia mengakui pluralisme agama, ada batasan-batasan tertentu yang diberikan oleh negara. Hal ini serupa dengan pendekatan 'messianic tendency' yang dilakukan oleh negara-negara Barat dalam menyebarkan nilai-nilai mereka, seperti kolonialisme yang beralasan membawa peradaban.
“Di kita, dengan membawa mereka ke jalan yang benar, kita sebut itu paradigma yang melegalkan diskriminasi terhadap agama yang lain,” ujarnya.
Burhani juga menyebutkan paradoks negara beragama dan berketuhanan yang menunjukkan ada korelasi yang tampak negatif antara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dengan keyakinan terhadap pentingnya agama.
“Negara yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi cenderung masyarakatnya menganggap agama tidak penting,” ujarnya, merujuk pada World Happiness Index yang menunjukkan bahwa negara-negara yang lebih bahagia sering kali adalah negara yang tidak terlalu religius.
Namun, Burhani juga mencatat bahwa negara-negara yang religius sering kali unggul dalam filantropi, termasuk Indonesia.
"Filantropi adalah salah satu kekuatan dari negara beragama seperti Indonesia," tambahnya.
Agama Hanya Fomalitas di Indonesia?
Di sisi lain Akademisi Universitas Satya Wacana Salatiga Izak Lattu mengatakan ada ada pluralitas tanpa kesetaraan dalam pengelolaan agama di Indonesia, yang menyebabkan kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan.
"Kita berhadapan dengan mayoritanisme yang sangat besar," ungkap Lattu, yang menyoroti bagaimana kelompok mayoritas sering kali menganggap kelompok minoritas sebagai 'denizen' atau warga negara setengah.
Lattu juga menekankan pentingnya memperkuat nasionalisme berdasarkan Pancasila.
“Kita harus kembali ke Pancasila sebagai akta hidup bersama yang harus ditempatkan sebagai political covenantal pluralism,” tegasnya, seraya menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Sementara itu, Direktur Interfidei Elga Sarapung mempertanyakan pengakuan terhadap keberagaman agama di Indonesia.
“Setelah 79 tahun merdeka, kita masih berputar di sekitar berapa agama yang diakui. Masih banyak Masyarakat yang menyebut hanya 5 agama yang diakui di Indonesia,” ungkapnya.
Dia mengamati bahwa meskipun konstitusi mengakui enam agama, praktik nyata di lapangan menunjukkan adanya diskriminasi terhadap agama minoritas seperti Baha’i dan Sikh yang dikategorikan sebagai penghayat kepercayaan.
“Praktik hidup beragama di Indonesia terjebak pada ritualitas tanpa memperhatikan substansi yang lebih dalam,” tambah Elga.
Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Zuly Qodir mengatakan, Indonesia dan beberapa negara sudah masuk dalam tahap post-sekularism yang mengarah formalisasi.Beragama sifatnya hanya artifisia, sehingga tidak mendorong pada motivasi orang menjadi progresif.
“Misalnya bagaimana tentang kemiskinan, bagaimana kemiskinan direspons oleh agama-agama di Indonesia. Ya karena sering ambil sifatnya yang formalistik,” pungkasnya.