Bre Redana: Media digital melahirkan delusi dan remeh temeh

Merdeka.com - The medium is the message (medium adalah pesan). Premis Marshall McLuhan dalam bukunya 'Understanding Media: The Extensions of Man' (1964) menjadi dasar pembelaan Bre Redana, wartawan senior Harian Kompas, atas berbagai kritik kepadanya setelah menulis artikel 'Inikah Senjakala Kami' di harian tempat dia bekerja pada 28 Desember 2015 lalu.
Dalam artikel itu, Bre mempertanyakan 'apakah ini akhir dari peradaban surat kabar cetak saat ini?' sambil mengkritik cara kerja, bahkan kualitas wartawan yang berkerja di media digital.
Dalam diskusi di kedai kopi kawasan Tebet, Jakarta Selatan, kemarin, Bre, dengan mengutip Mcluhan, menyatakan medium menentukan segala-galanya.
-
Apa saja yang sedang trending? Konten AI, yang mencakup penggunaan kecerdasan buatan untuk membuat konten seperti teks, gambar, dan video, sedang naik daun dalam beberapa tahun terakhir.
-
Apa yang menjadi trending saat ini? 35 Ucapan Selamat Wisuda Islami yang Sarat Doa dan Harapan, Cocok Dibagikan ke Kerabat Berikut 30 ucapan selamat wisuda islami yang bisa Anda jadikan sebagai pedoman untuk berpesan ke kerabat dan orang-orang terdekat.
-
Apa yang lagi trending? Kumpulan pantun untuk ucapan hari ibu yang manis dan penuh makna.
-
Apa yang sedang trending saat ini? Kata-kata bijak tetap tenang ini mengingatkan kita bahwa ketenangan adalah kekuatan besar dalam menghadapi berbagai situasi hidup.
-
Apa yang sedang tren? 'Di hari yang penuh berkah ini, Selamat Lebaran, Bapak/Ibu. Semoga kita selalu dalam naungan-Nya.'
"Sehingga asosiasinya seperti dikatakan McLuhan berita hubungannya dengan surat kabar, musik hubungannya dengan radio, show hubungannya dengan televisi, kalau konversasi hubungannya dengan telepon. Hanya ini yang diomongkan, karena saat itu internet belum lahir," kata Bre yang serius menjelaskan dengan menggunakan slide.
Menurut Bre, saat ini yang selalu dibicarakan orang, termasuk yang mengkritiknya, hanyalah konten, bukan teknologi sebagai medium. Padahal, kata dia, teknologi membawa konsekuensi-konsekuensi tersendiri.
"Setiap kali muncul teknologi, orang melupakan mediumnya," ujarnya.

"Padahal menurut McLuhan medium is like the juicy piece of meat carried by the burglar to distract the watchdog of the mind (medium seperti sepotong daging segar yang dibawa pencuri untuk mengalihkan 'anjing penjaga' pikiran)," kata Bre mengutip McLuhan.
Bre menegaskan, pikiran adalah kesadaran. "Kesadaran ini yang dialihkan oleh medium, orang tidak pernah sadar," ujar dia.
Dia memaparkan, perbedaan mekanisme operasional indera manusia ketika membaca di media cetak dengan media digital.
"Kalau anda baca buku, ada tinta yang tercetak di atas kertas, ini kan beda dengan anda membaca pixel di atas layar hitam yang menyala terang," ujar dia.
Mengutip teori fotografi, Bre mengatakan, mata adalah pixel yang bisa menangkap bentuk, warna dan dimensi.
"Kalau anda membaca layar digital, pixel ketemu pixel, kalau baca layar digital bagian mata putih kita tidak bekerja," kata dia.
Tentu, kata Bre, dengan dengan perbedaan-perbedaan mekanisme operasional indra tersebut, akan berpengaruh kepada bagaimana otak manusia bekerja. "Ini bukan soal baik atau buruk, tapi soal perbedaan," kata dia.
Menurut Bre, perbedaan membaca media cetak dan digital ada pada linearitas (linearity) versus hypertext (link). Membaca media cetak, katanya, ada proses ketenggelaman (immersion) pembaca terhadap teks dalam objek bacaan.
Hal ini, menurut dia, tidak terjadi saat seseorang membaca media digital karena meloncat dari satu laman ke laman lain karena ada hypertext.

"Jadi ibaratnya membaca media cetak itu menyelam, sedangkan membaca media digital itu seperti berselancar atau bermain jetski," papar.
Bre mengatakan, persoalan kesadaran inilah yang menjadi alasan mengapa dirinya berpendapat media cetak harus dipertahankan.
Jika media cetak menghadirkan kesadaran, kata Bre, media digital justru melahirkan delusi.
"Dunia digital itu sebuah proses delusi, kondisi, lalu output, kalau jurnalisme kondisi, situasi, hadir, masuk dan merasakan," ujar dia.
Delusi dalam dunia digital, kata Bre, karena manusia tidak berhubungan langsung dengan manusia.
"Tapi berhubungan gadget, terpisah dengan dunia kita, terlebih lagi saraf-saraf kita tidak bekerja ketika berkomunikasi dengan ini (gadget)."
Dia mencontohkan, bagaimana delusi bertemu dengan sebuah kondisi, seperti teror bom Sarinah.
"Delusi dan kondisi bertemu seketika dan langsung mengeluarkan output, langsung nulis, makanya simpang siur informasinya," kata Bre tentang wartawan online yang melaporkan tanpa hadir di lapangan.
Karena dalam dunia digital yang beroperasi adalah delusi dalam sebuah kondisi, kata Bre, yang terjadi bukan lagi logika (logic), tetapi hanya pada wilayah perasaan.
"Makanya kalau dulu ada listeners, readers, viewers, sekarang muncul istilah haters," ujar Bre.
Jika media cetak era Gutenberg telah menghadirkan daya imajinatif yang melahirkan pencerahan (renaissance) sampai ke era postmodernism, kata Bre, media digital menghadirkan remeh-temeh (trivialities).
"Dari imaginative pursuit (pengejaran imajinatif), kita sedang menuju zaman trivialities pursuit (pengejaran remeh-temeh). Makanya ada teror, yang dibicarakan sepatu Gucci," paparnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Ignatius Haryanto tidak sependapat dengan Bre. Menurutnya, ketika medium mengonstruksikan pesan apa yang akan muncul, maka yang diperlukan adalah kecerdasan-kecerdasan wartawan untuk mengemas pada aneka medium yang berbeda-beda.
"Media sosial pendek, yang harus punya keterampilan menulis pendek. Sebaliknya ketika harus menulis panjang dan naratif, juga harus mampu," ujar Haryanto di tempat yang sama.
"Jadi wartawan sekarang harus punya kemampuan yang lebih banyak dengan medium-medium yang ada," ujarnya.
Salain itu, kata Haryanto, perlu juga dilakukan terobosan pada media baru. Seperti yang dilakukan ProPublica, media online di AS, yang meliput dengan sangat baik dan komprehensif mengenai badai Katarina di negara tersebut, sehingga memenangi hadiah Pulitzer.
"ProPublica media non-print pertama yang mendapatkan Pulitzer," ujar dia.
Wartawan senior Sinar Harapan, Aristides Katoppo, mengatakan harus dibedakan antara senjakala surat kabar dan jurnalisme itu sendiri. Dia mencontohkan keberhasilan majalah The Economist dan surat kabar The Guardian, meski kini telah berganti platform.
"Saya yakin di tengah cuaca mendung, selalu ada harapan yang masih bisa dibagikan," ujarnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

FOMO adalah rasa takut tertinggal pengalaman yang terjadi di sekitarnya. Namun tahukah Anda bahwa ketakutan ini ternyata berbahaya bagi kesehatan mental?
Baca Selengkapnya
Hampir seluruh aksi keluarga Sultan Andara, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selalu jadi sorotan publik.
Baca Selengkapnya
Sebaiknya kita lebih selektif membedakan antara kebutuhan dan keinginan.
Baca Selengkapnya
Kenakan jam tangan mewah yang harganya ratusan juta rupiah, pedagang putu ini dicuragi sebagai intel.
Baca Selengkapnya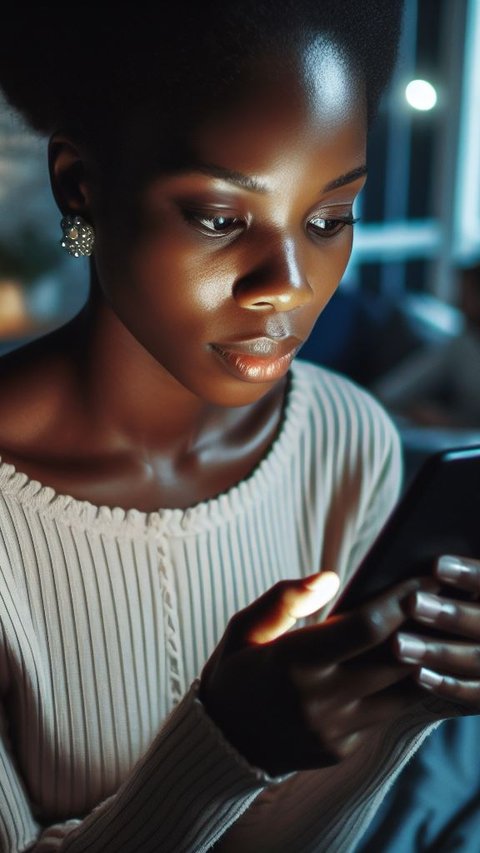
Brain rot menggunakan istilah yang sedang populer di tahun ini. Kenali arti dan dampaknya.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani kasih paham soal video viral penagihan pajak oleh Bea Cukai kepada WNI yang membeli sepatu seharga Rp10 juta di luar negeri.
Baca Selengkapnya
Niat ingin membeli sepatu untuk liburan, wanita ini justru dibuat heran. Pasalnya, sepatu yang datang malah seperti ini.
Baca Selengkapnya
Floating duck syndrome merupakan kondisi ketika menganggap kesuksesan orang lain bisa dicapai dengan mudah.
Baca Selengkapnya